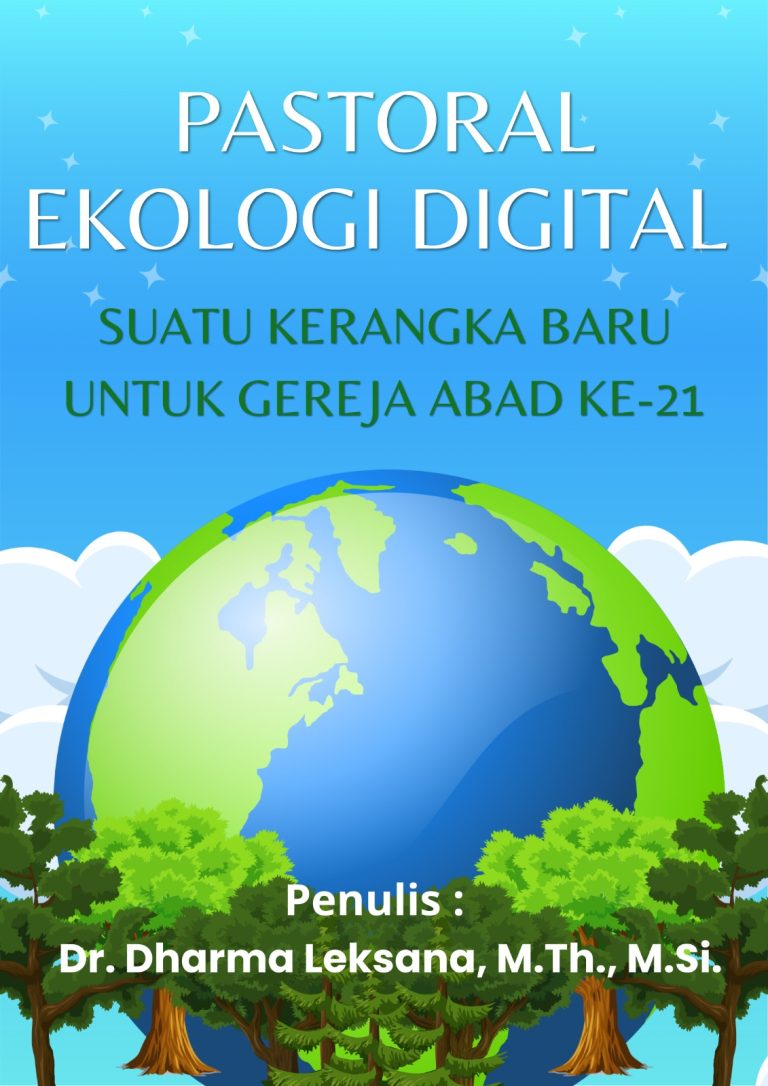Oleh : Dharma Leksana, S.Th., M.Si.
Wartagereja.co.id – Jakarta, Paulo Freire (1921-1997) merupakan seorang filsuf, pendidik, dan teoretikus kritis asal Brasil yang gagasannya telah memberikan pengaruh mendalam pada diskursus pendidikan global. Pengalaman hidupnya, terutama keterlibatannya dengan kaum miskin dan buta huruf selama masa Depresi Besar dan periode-periode berikutnya, secara fundamental membentuk keprihatinannya terhadap isu-isu ketidakadilan sosial dan penindasan.¹ Pemikirannya, yang paling terkenal terartikulasi dalam Pedagogi Kaum Tertindas, menantang model pendidikan tradisional dan mengusulkan sebuah visi pendidikan sebagai alat pembebasan manusia.
Di sisi lain, kita hidup dalam era digital yang ditandai dengan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi ke hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk ranah spiritual dan keagamaan. Fenomena ini melahirkan bidang kajian baru yang dikenal sebagai “Teologi Digital,” yang berupaya merefleksikan secara teologis interaksi antara iman, praktik keagamaan, dan budaya digital.² Munculnya ruang-ruang virtual untuk komunitas iman, penyebaran ajaran melalui media sosial, hingga isu otoritas keagamaan dalam jaringan, menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru bagi ekspresi dan penghayatan iman.
Dalam artikel ini penulis akan berdiskusi dengan Paulo Freire untuk menjembatani pemikiran Freire dengan konteks teologi digital. Pertanyaan sentral yang diajukan adalah: Sejauh mana konsep pendidikan yang membebaskan menurut Paulo Freire relevan secara signifikan untuk memahami, mengkritisi, dan membangun praksis teologi digital yang lebih adil dan humanis? Untuk menjawab pertanyaan ini, Penulis akan terlebih dahulu mengulas kerangka pemikiran pendidikan Freire, kemudian membahas lanskap dan isu-isu kunci dalam teologi digital, dan akhirnya menganalisis titik-titik temu dan relevansi kritis antara keduanya.
Kerangka Pemikiran Pendidikan Paulo Freire
Inti dari kritik Freire adalah penolakannya terhadap apa yang ia sebut sebagai “konsep pendidikan gaya bank” (banking concept of education). Dalam model ini, guru dipandang sebagai pemilik pengetahuan yang “menabungkan” informasi ke dalam pikiran siswa yang dianggap sebagai wadah kosong dan pasif.³ Hubungan yang tercipta bersifat vertikal, menindas, dan meniadakan kapasitas kritis serta kreativitas siswa. Pendidikan semacam ini, menurut Freire, melanggengkan status quo dan berfungsi sebagai alat domestikasi, bukan pembebasan.
Sebagai alternatif, Freire mengusulkan “pendidikan hadap masalah” (problem-posing education). Model ini bersifat dialogis, di mana guru dan siswa bersama-sama menjadi subjek pembelajar yang secara kritis mengkaji realitas dunia mereka.⁴ Proses belajar berpusat pada pengungkapan masalah-masalah konkret yang dihadapi dalam kehidupan, yang kemudian dianalisis melalui dialog untuk memahami akar penyebabnya dan mencari solusi transformatif. Beberapa konsep kunci dalam pedagogi Freire meliputi:
- Conscientização (Penyadaran/Kesadaran Kritis): Ini adalah proses di mana individu dan komunitas belajar untuk memahami secara kritis kontradiksi sosial, politik, dan ekonomi dalam realitas mereka, serta mengambil tindakan untuk melawan elemen-elemen yang menindas.⁵ Ini bukan sekadar kesadaran pasif, tetapi kesadaran yang mendorong transformasi.
- Dialog: Bagi Freire, dialog adalah esensi dari pendidikan yang membebaskan. Ini adalah pertemuan antara manusia, yang dimediasi oleh dunia, untuk “menamai” dunia tersebut. Dialog mengandaikan adanya cinta, kerendahan hati, iman pada sesama, harapan, dan pemikiran kritis.⁶ Hubungan guru-siswa bersifat horizontal dan saling belajar.
- Praksis: Konsep ini merujuk pada hubungan dialektis antara refleksi (pemahaman kritis terhadap realitas) dan aksi (tindakan transformatif di dunia). Pendidikan sejati, menurut Freire, harus melibatkan kedua elemen ini secara tak terpisahkan.⁷ Tanpa aksi, refleksi menjadi verbalisme; tanpa refleksi, aksi menjadi aktivisme buta.
- Pembebasan (Liberation): Tujuan akhir dari pendidikan Freirean adalah pembebasan manusia dari struktur-struktur yang menindas, baik eksternal maupun internal (mentalitas tertindas). Ini adalah proses menjadi lebih manusiawi (humanization) melalui perjuangan melawan dehumanisasi.⁸
Karya-karya utama seperti Pedagogi Kaum Tertindas (1968) dan Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan (1967) menjadi pilar yang menjelaskan secara mendalam konsep-konsep ini dan bagaimana menerapkannya dalam konteks pendidikan kaum tertindas.⁹
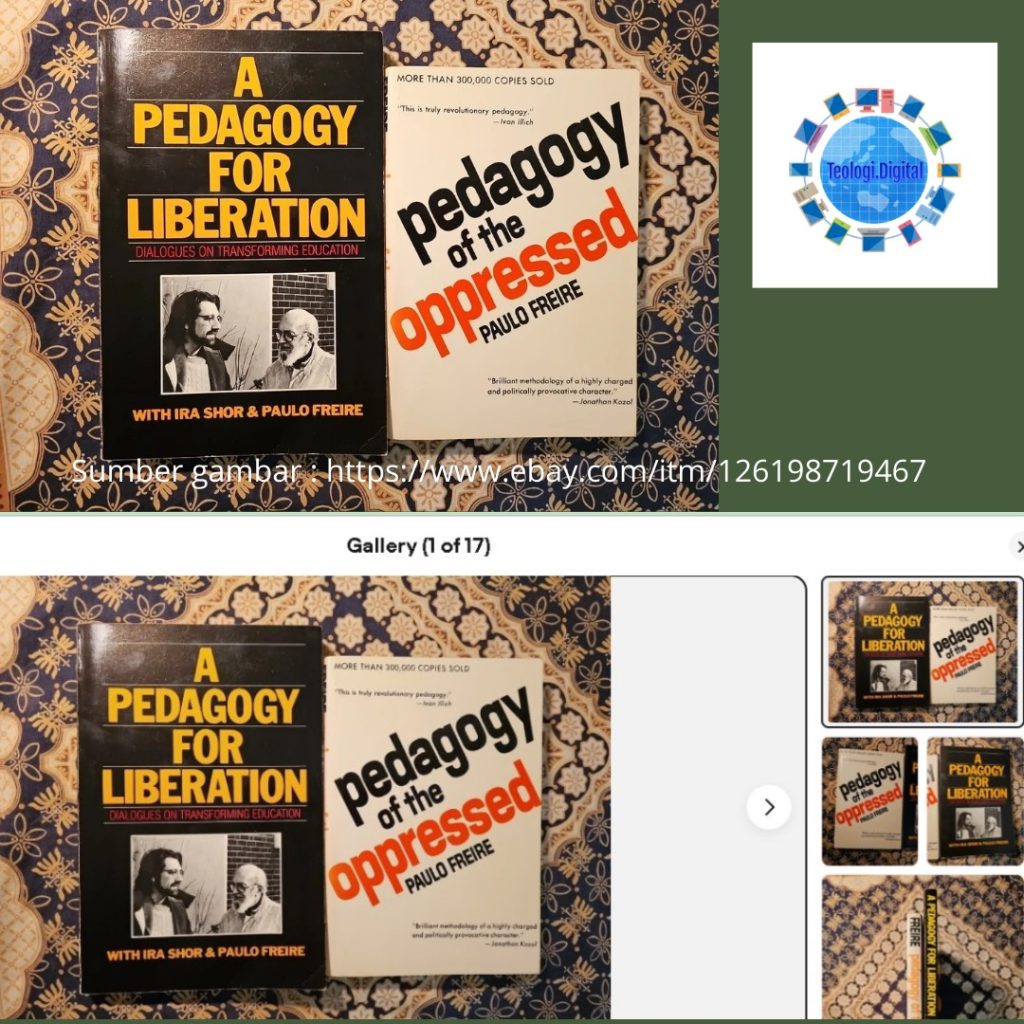
Memahami Lanskap Teologi Digital
Teologi digital adalah bidang interdisipliner yang relatif baru, mengeksplorasi persimpangan antara teologi (refleksi sistematis tentang Tuhan, iman, kemanusiaan, dan dunia) dengan teknologi, budaya, dan praktik digital.¹⁰ Bidang ini tidak hanya melihat bagaimana teknologi digunakan oleh lembaga keagamaan, tetapi juga bagaimana budaya digital itu sendiri membentuk ulang pemahaman dan praktik keimanan. Beberapa isu kunci yang menjadi perhatian dalam teologi digital antara lain:
- Komunitas dan Relasi: Bagaimana komunitas iman terbentuk dan dipelihara secara online? Apa implikasi teologis dari relasi yang termediasi layar (misalnya, kehadiran, inkarnasi, persekutuan)?¹¹
- Otoritas dan Pengetahuan: Bagaimana otoritas keagamaan dinegosiasikan dalam ruang digital yang cenderung datar dan partisipatif? Bagaimana jemaat mengakses dan menginterpretasi informasi keagamaan di tengah arus informasi yang masif (termasuk hoaks dan disinformasi)?¹²
- Identitas dan Spiritualitas Digital: Bagaimana individu membentuk identitas keagamaan mereka secara online? Bagaimana praktik spiritual (doa, ibadah, meditasi) diadaptasi atau diubah oleh teknologi digital?¹³
- Kesenjangan Digital dan Keadilan Sosial: Siapa yang memiliki akses terhadap teknologi dan literasi digital, dan siapa yang tertinggal? Bagaimana kesenjangan ini merefleksikan dan memperburuk ketidakadilan sosial yang ada, dan apa respons teologis terhadapnya?¹⁴
- Etika Digital: Tantangan etis terkait privasi data, kecerdasan buatan, penyebaran ujaran kebencian, dan penggunaan teknologi untuk pengawasan atau manipulasi dalam konteks keagamaan.
Teologi digital, dengan demikian, bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana menjadi “gereja” atau “umat beriman” di tengah-tengah revolusi digital, sambil tetap setia pada inti ajaran dan nilai-nilai teologis.
Menjalin Relevansi: Pendidikan Freirean dalam Konteks Teologi Digital
Pemikiran Paulo Freire menawarkan kerangka kerja yang sangat relevan untuk menganalisis dan membentuk praksis teologi digital yang membebaskan:
- Mengkritik “Teologi Digital Gaya Bank”: Konsep “sistem bank” Freire dapat digunakan untuk mengkritik model komunikasi teologis digital yang bersifat satu arah, di mana lembaga atau figur otoritas sekadar “menuangkan” konten keagamaan kepada audiens yang pasif. Platform digital yang hanya digunakan untuk siaran khotbah tanpa interaksi, atau penggunaan media sosial yang sekadar mengumpulkan “like” tanpa pendalaman refleksi, berisiko menjadi bentuk baru dari “pendidikan gaya bank”. Sebaliknya, teologi digital yang membebaskan akan mendorong platform yang memungkinkan partisipasi aktif, dialog, dan produksi pengetahuan bersama oleh seluruh komunitas iman.
- Mendorong Dialog dan Conscientização Digital: Prinsip dialog Freire sangat krusial di era digital. Bagaimana menciptakan ruang online yang aman dan kondusif untuk dialog teologis yang otentik, yang melampaui perdebatan dangkal atau polarisasi? Teologi digital perlu secara sadar memfasilitasi dialog yang penuh hormat, kritis, dan transformatif. Lebih jauh, conscientização dalam konteks ini berarti membangkitkan kesadaran kritis tidak hanya tentang isu-isu sosial di “dunia nyata”, tetapi juga tentang struktur kekuasaan yang bekerja dalam ekosistem digital itu sendiri. Ini termasuk kesadaran tentang algoritma yang membentuk persepsi kita, bias dalam teknologi, kepemilikan data, dan terutama, kesenjangan digital sebagai isu keadilan teologis. Umat perlu disadarkan bahwa akses dan partisipasi digital bukanlah netral, melainkan medan perjuangan keadilan.¹⁵
- Mengembangkan Praksis Teologi Digital yang Membebaskan: Kerangka praksis Freire (refleksi-aksi) menantang teologi digital untuk tidak berhenti pada refleksi akademis atau diskusi online semata. Bagaimana refleksi teologis tentang realitas digital dapat diterjemahkan menjadi aksi konkret? Contohnya bisa beragam: menggunakan platform digital untuk mengorganisir aksi sosial atau advokasi keadilan, menciptakan konten digital yang menyuarakan narasi kaum marginal, membangun komunitas online yang inklusif dan suportif, atau mengembangkan program literasi digital kritis bagi jemaat. Praksis teologi digital berarti menggunakan teknologi sebagai alat untuk transformasi sosial yang diinspirasi oleh nilai-nilai iman.
- Menyoroti Dimensi Pembebasan dalam Kesenjangan Digital: Keprihatinan utama Freire terhadap kaum tertindas menemukan gaung yang kuat dalam isu kesenjangan digital (digital divide). Ketidaksetaraan akses terhadap perangkat, konektivitas internet, dan keterampilan digital menciptakan bentuk baru dari marginalisasi dan penindasan di abad ke-21. Dari perspektif Freirean, teologi digital tidak bisa mengabaikan realitas ini. Upaya pembebasan harus mencakup perjuangan untuk kesetaraan akses digital, memastikan bahwa teknologi tidak semakin memperlebar jurang antara yang “memiliki” dan yang “tidak memiliki” dalam konteks informasi, partisipasi, dan bahkan ekspresi iman. Teologi digital yang membebaskan adalah teologi yang secara aktif memperjuangkan inklusi digital.
Perspektif Kritis Paulo Freire bagi Teologi Digital
Menerapkan kerangka Freire dalam teologi digital bukannya tanpa tantangan. Sifat ruang digital yang seringkali anonim, cepat, dan terfragmentasi dapat menghambat dialog yang mendalam. Algoritma media sosial dapat menciptakan “gelembung filter” (filter bubbles) yang justru mempersempit cakrawala dan menghalangi kesadaran kritis. Selain itu, potensi teknologi digital untuk digunakan sebagai alat kontrol, pengawasan, dan penyebaran ideologi yang menindas juga merupakan ancaman nyata yang perlu diwaspadai.
Last but not least, Meskipun Paulo Freire mengembangkan teorinya jauh sebelum era digital mencapai puncaknya, prinsip-prinsip pedagogi kritis dan pembebasannya menawarkan relevansi yang luar biasa bagi pengembangan teologi digital saat ini. Kritiknya terhadap “sistem bank,” penekanannya pada dialog otentik, panggilan untuk kesadaran kritis (conscientização), dan dorongan untuk praksis transformatif memberikan lensa yang sangat dibutuhkan untuk menavigasi kompleksitas iman di era digital.
Dengan mengadopsi perspektif Freirean, teologi digital dapat bergerak melampaui sekadar penggunaan teknologi sebagai alat baru untuk metode lama. Ia dapat menjadi sebuah refleksi dan praktik teologis yang secara kritis membongkar struktur kekuasaan dalam ruang digital, memberdayakan suara-suara yang terpinggirkan (termasuk mereka yang terdampak kesenjangan digital), mendorong partisipasi otentik komunitas iman, dan mengarahkan penggunaan teknologi untuk tujuan pembebasan dan humanisasi yang lebih besar. Pada akhirnya, relevansi Freire terletak pada pengingat abadinya bahwa pendidikan—dan juga teologi—pada hakikatnya haruslah menjadi praktik pembebasan. (Dh.L./Red.***)
Catatan Kaki
¹ Gadotti, Moacir. Reading Paulo Freire: His Life and Work. Diterjemahkan oleh John Milton. Albany: State University of New York Press, 1994. Informasi biografis dasar juga diambil dari materi yang disediakan pengguna. ² Lihat misalnya, Campbell, Heidi A., ed. Digital Theology: Understanding Religious Practice in New Media Worlds. London: Routledge, 2016; Garner, Stephen, and Heidi Campbell. Networked Theology: Negotiating Faith in Digital Culture. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2016. ³ Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Edisi Ulang Tahun ke-30. Diterjemahkan oleh Myra Bergman Ramos. New York: Continuum, 2000, Bab 2. ⁴ Ibid. ⁵ Freire, Paulo. Education for Critical Consciousness. New York: Seabury Press, 1973. ⁶ Freire, Pedagogy of the Oppressed, Bab 3. ⁷ Ibid., Bab 1. ⁸ Ibid., Bab 1. ⁹ Freire, Paulo. Education as the Practice of Freedom. Diterbitkan bersama dengan Education for Critical Consciousness. New York: Continuum, 1985 (Cetakan ulang dari edisi 1967 dan 1973). ¹⁰ Hutchings, Tim. “Creating Church Online: Ritual, Community and New Media”. London: Routledge, 2017; Phillips, Peter. “Defining Digital Theology: Digital Humanities, Digital Religion and the Particular Work of the Digital Theologian.” Open Theology 5, no. 1 (2019): 29-43. ¹¹ Campbell, Heidi A. “Religion and the Internet.” Communication Research Trends 26, no. 1 (2007): 3–24. ¹² Lövheim, Mia, and Heidi Campbell. “Introduction: Considering the Role of Religion in Online Communication.” Information, Communication & Society 20, no. 1 (2017): 1–8. ¹³ Hoover, Stewart M. “Religion in the Media Age.” London: Routledge, 2006. ¹⁴ Kurlberg, Jonas. “Digital Theology and the Digital Divide: A Reflection from the Context of Development Studies.” Dalam Missio Dei in a Digital Age, diedit oleh Ross Clifford dkk. London: SCM Press, 2019. ¹⁵ Bisa dikembangkan dengan merujuk pada konsep ‘digital justice’ atau keadilan digital.
Daftar Pustaka
- Campbell, Heidi A., ed. Digital Theology: Understanding Religious Practice in New Media Worlds. London: Routledge, 2016.
- Campbell, Heidi A. “Religion and the Internet.” Communication Research Trends 26, no. 1 (2007): 3–24.
- Freire, Paulo. Education as the Practice of Freedom. Diterbitkan bersama dengan Education for Critical Consciousness. New York: Continuum, 1985. (Cetakan ulang dari edisi 1967 dan 1973).
- Freire, Paulo. Education for Critical Consciousness. New York: Seabury Press, 1973.
- Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Edisi Ulang Tahun ke-30. Diterjemahkan oleh Myra Bergman Ramos. New York: Continuum, 2000.
- Gadotti, Moacir. Reading Paulo Freire: His Life and Work. Diterjemahkan oleh John Milton. Albany: State University of New York Press, 1994.
- Garner, Stephen, and Heidi Campbell. Networked Theology: Negotiating Faith in Digital Culture. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2016.
- Hoover, Stewart M. Religion in the Media Age. London: Routledge, 2006.
- Hutchings, Tim. Creating Church Online: Ritual, Community and New Media. London: Routledge, 2017.
- Kurlberg, Jonas. “Digital Theology and the Digital Divide: A Reflection from the Context of Development Studies.” Dalam Missio Dei in a Digital Age, diedit oleh Ross Clifford dkk. London: SCM Press, 2019.
- Lövheim, Mia, and Heidi Campbell. “Introduction: Considering the Role of Religion in Online Communication.” Information, Communication & Society 20, no. 1 (2017): 1–8.
- Phillips, Peter. “Defining Digital Theology: Digital Humanities, Digital Religion and the Particular Work of the Digital Theologian.” Open Theology 5, no. 1 (2019): 29-43.