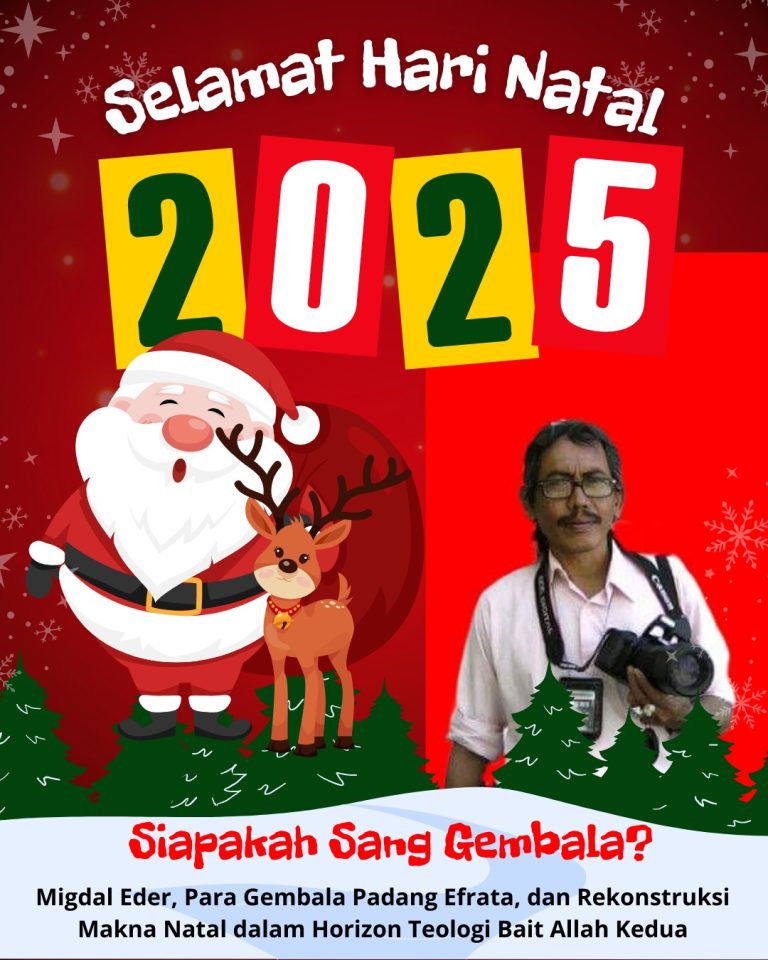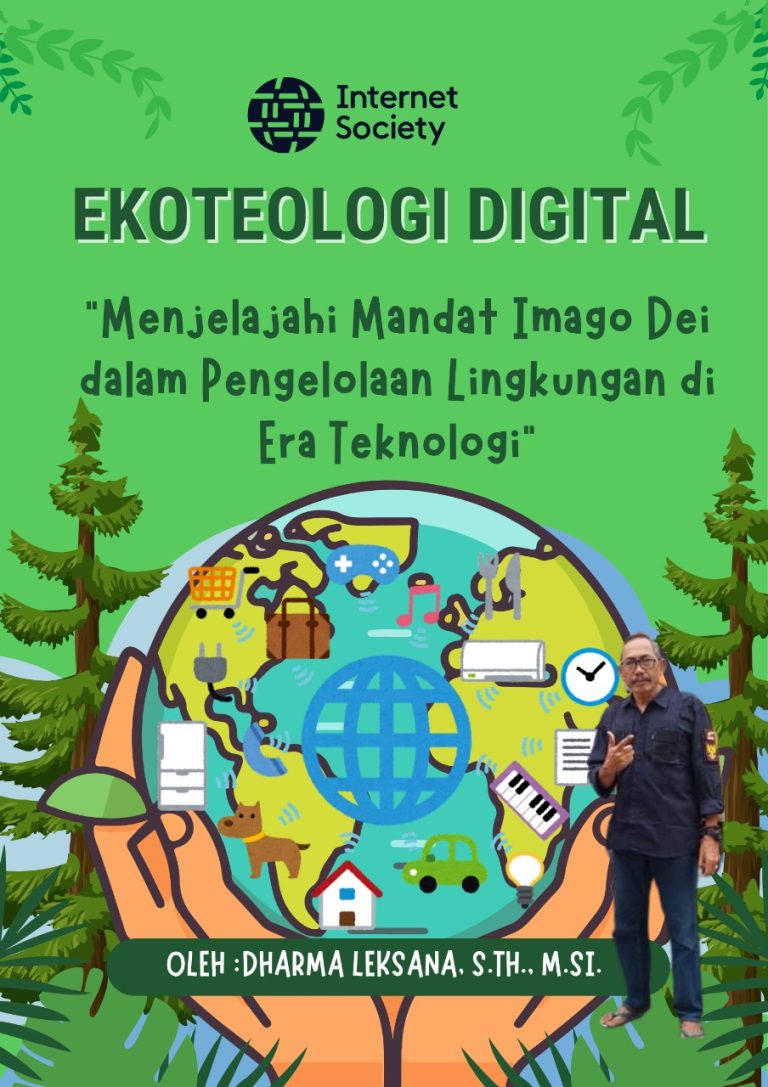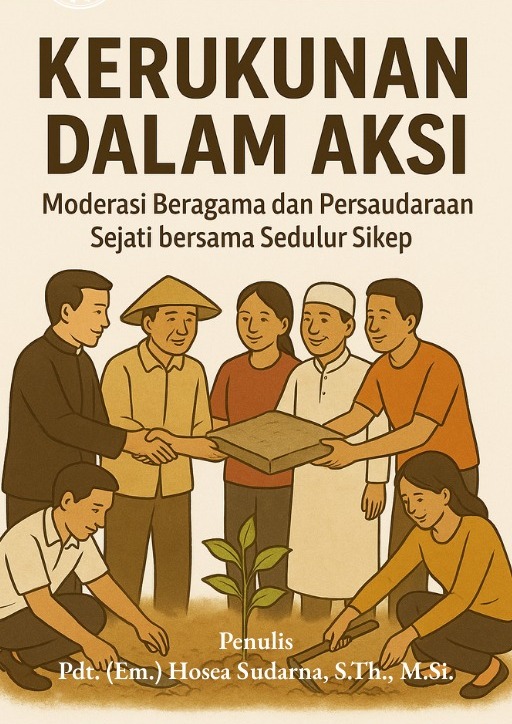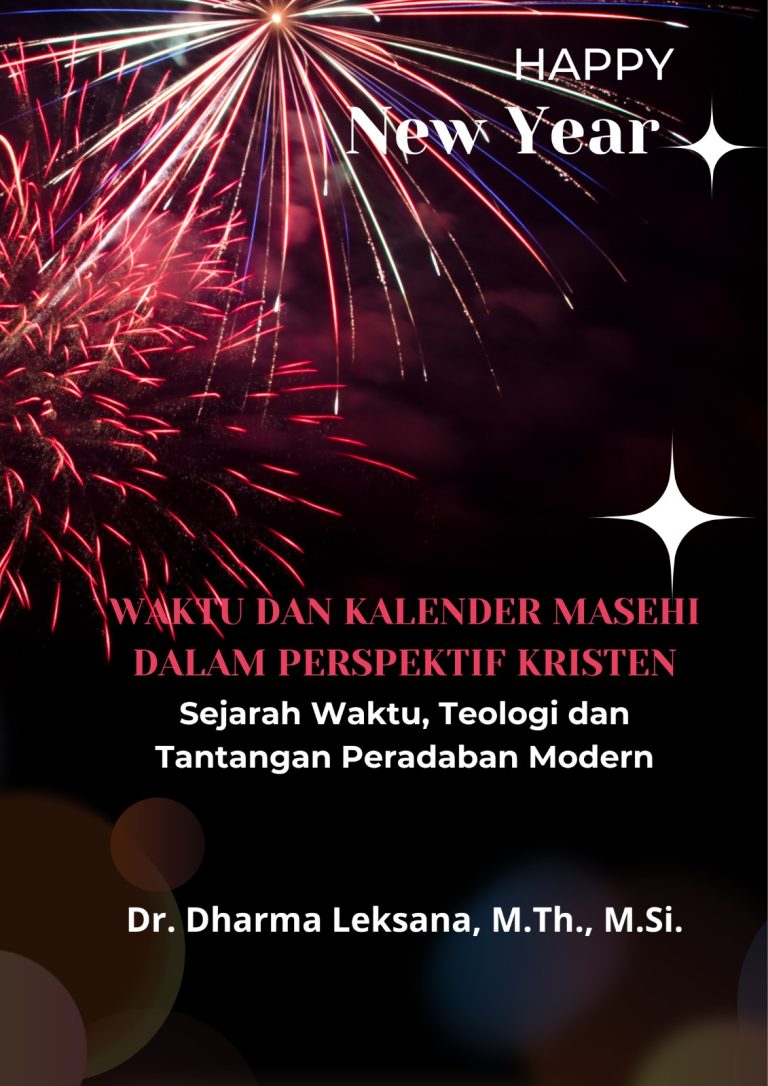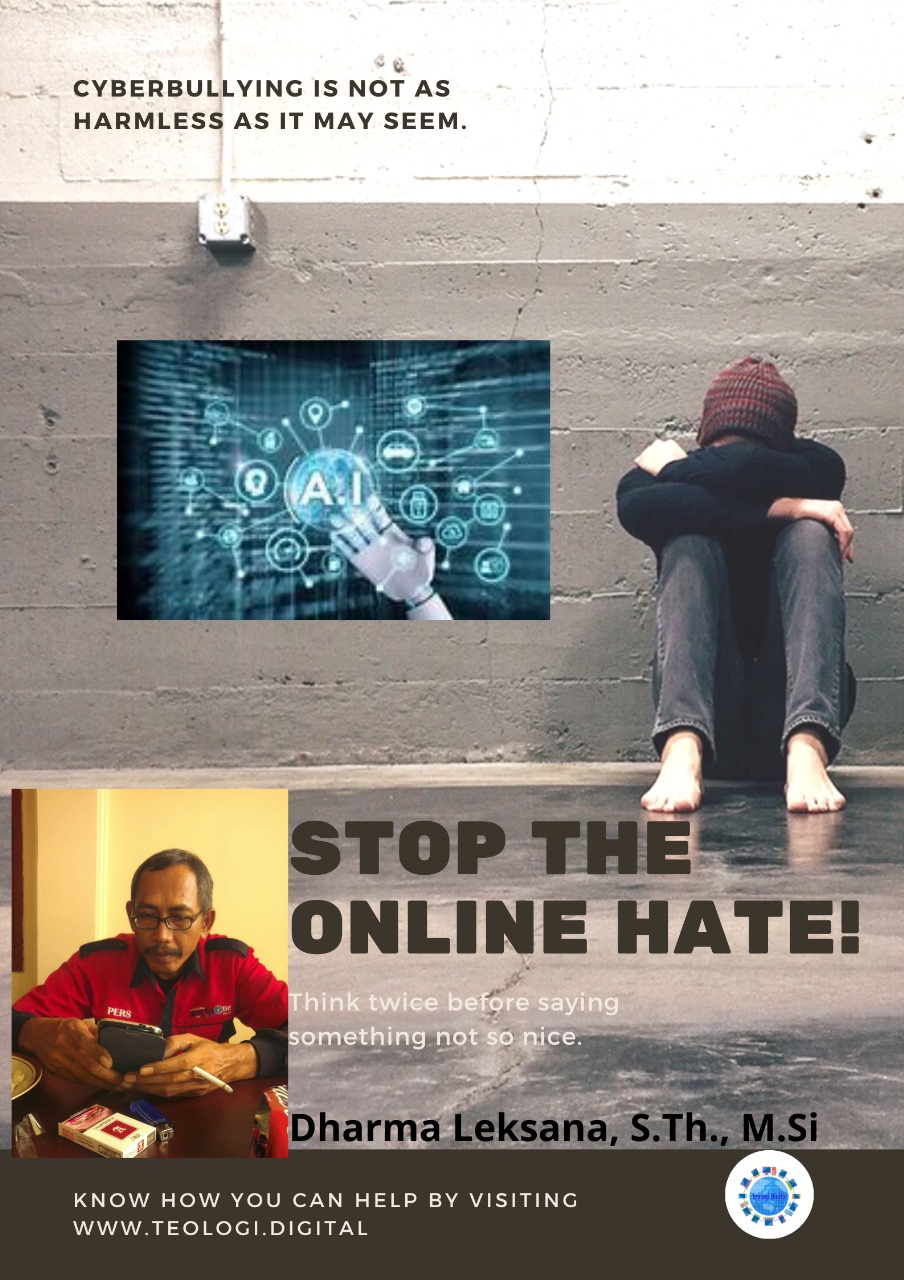
Oleh : Dharma Leksana, S.Th., M.Si.
Wartagereja.com – Jakarta, Era digital, yang ditandai dengan penetrasi internet dan media sosial yang masif, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara anak-anak berinteraksi, belajar, dan bersosialisasi. Namun, di balik manfaatnya, teknologi digital juga menghadirkan sisi gelap berupa ancaman kekerasan terhadap anak dalam bentuk-bentuk baru yang lebih kompleks.
Kekerasan pada anak di era digital, khususnya kekerasan seksual, cyberbullying, dan penyebaran konten seksual tanpa izin, merupakan ancaman serius yang memerlukan perhatian komprehensif (PSGA UIN Malang, 2025; Plato Foundation, 2024). Anak-anak, dengan karakteristik keingintahuan yang tinggi dan pemahaman risiko yang terkadang terbatas, menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan di ruang siber.
Fenomena kekerasan terhadap anak bukanlah isu baru. Jauh sebelum era digital, PBB telah menyoroti peningkatan skala berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak di seluruh dunia dan menyerukan penguatan komitmen global (Studi PBB, 2006).
Di Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat berbagai kasus kekerasan, bahkan yang dilakukan oleh orang terdekat (Harian Kedaulatan Rakyat, 2009; Seto Mulyadi, Komnas PA).
Data terkini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Indonesia cenderung meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024, dengan anak perempuan menjadi korban mayoritas (24.999 kasus) dibandingkan anak laki-laki (6.228 kasus) (KemenPPPA, 2024; NU Online).
Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 juga mengungkap bahwa 50,78% anak usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya (UNICEF Indonesia, 2024; Detiknews:BPS Indonesia). Peningkatan signifikan terlihat dibandingkan tahun 2021, khususnya pada kekerasan emosional, fisik, dan seksual (Antara News).
Kekerasan daring memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan kekerasan konvensional. Pelaku dapat bersembunyi di balik anonimitas, jangkauan korban lebih luas, dan jejak digital kekerasan sulit dihilangkan.
Kekerasan daring ini seringkali tidak berhenti di dunia maya, namun dapat berlanjut menjadi kekerasan fisik dan meninggalkan dampak psikologis mendalam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengupas tuntas permasalahan kekerasan terhadap anak di era digital, meliputi jenis-jenisnya, dampak yang ditimbulkan, faktor-faktor risiko, serta upaya pencegahan dan penanganan yang efektif.
Kajian Pustaka dan Konsep Dasar
1. Definisi Kekerasan Terhadap Anak Kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik, seksual, atau emosional, penelantaran, eksploitasi komersial atau lainnya, yang mengakibatkan kerugian atau ancaman terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabatnya, dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (UNICEF & Save the Children). UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.
2. Era Digital dan Implikasinya bagi Anak Era digital merujuk pada periode waktu dalam sejarah manusia yang ditandai oleh pergeseran dari industri tradisional ke ekonomi berbasis informasi dan komunikasi teknologi. Bagi anak-anak, era ini berarti akses yang lebih mudah ke informasi, platform untuk berekspresi, dan sarana untuk bersosialisasi. Namun, paparan terhadap konten negatif, interaksi dengan orang asing yang berniat jahat, dan risiko privasi menjadi tantangan tersendiri.
Pembahasan
A. Jenis-Jenis Kekerasan Daring Terhadap Anak
Teknologi digital membuka pintu bagi pelaku untuk melakukan kekerasan dalam berbagai bentuk (redbridgescp.org.uk). Jenis-jenis kekerasan daring yang paling umum mengancam anak-anak meliputi:
- Cyberbullying: Perundungan yang terjadi di dunia maya melalui media sosial, pesan singkat, aplikasi perpesanan, game online, atau platform online lainnya. Bentuknya bisa berupa ejekan, hinaan, ancaman, penyebaran rumor, hingga pengucilan dari grup online.
- Grooming Online: Upaya pelaku untuk membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan anak melalui internet, seringkali dengan menyamar atau memanipulasi. Tujuannya adalah untuk melakukan eksploitasi atau kekerasan seksual, baik secara daring maupun memancing pertemuan luring.
- Penyebaran Konten Seksual Tanpa Izin (Non-Consensual Dissemination of Intimate Images/NCII): Ini mencakup pembuatan, penyebaran, dan pembagian materi seksual anak-anak (foto atau video) tanpa izin atau persetujuan mereka. Termasuk di dalamnya adalah sextortion, di mana pelaku mengancam akan menyebarkan konten intim korban jika tidak menuruti kemauannya.
- Pelecehan dan Eksploitasi Seksual Online: Tindakan pelecehan seksual (misalnya, komentar bernuansa seksual yang tidak diinginkan, pengiriman gambar eksplisit) dan eksploitasi seksual (misalnya, memaksa anak melakukan tindakan seksual di depan kamera, perdagangan anak untuk tujuan seksual melalui platform online) yang dilakukan melalui media digital.
B. Dampak Kekerasan Daring pada Anak
Kekerasan daring dapat meninggalkan luka mendalam dan berdampak jangka panjang pada anak, baik secara psikologis, fisik, maupun kehidupan sosialnya:
- Dampak Psikologis: Korban kekerasan daring seringkali mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi berat, kecemasan kronis, perasaan malu dan bersalah, penurunan harga diri, kesulitan tidur, mimpi buruk, dan gangguan emosi lainnya. Mereka mungkin juga menunjukkan perilaku menarik diri dan kesulitan mempercayai orang lain.
- Dampak Fisik: Meskipun kekerasan terjadi di ranah daring, dampaknya bisa bersifat fisik. Cyberbullying yang ekstrem dapat memicu tindakan menyakiti diri sendiri. Selain itu, predator online yang berhasil melakukan grooming dapat mengajak korban bertemu secara luring, yang berpotensi mengakibatkan kekerasan fisik atau seksual secara langsung.
- Dampak Terhadap Kehidupan: Pengalaman menjadi korban kekerasan daring dapat mengganggu perkembangan sosial dan akademik anak. Mereka mungkin mengalami penurunan konsentrasi di sekolah, isolasi sosial, kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai. Dalam kasus yang paling parah, kekerasan daring dapat memicu pikiran atau tindakan bunuh diri.
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerentanan Anak di Era Digital
Beberapa faktor berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan anak terhadap kekerasan di era digital:
- Kebutuhan untuk Terhubung dan Bersosialisasi: Anak-anak dan remaja memiliki kebutuhan alami untuk terhubung dengan teman sebaya dan merasa diterima. Media sosial dan platform online seringkali menjadi sarana utama untuk memenuhi kebutuhan ini, namun juga membuka ruang bagi interaksi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Kurangnya Pemahaman tentang Keamanan Daring dan Privasi: Banyak anak belum sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan penggunaan internet, seperti pentingnya menjaga informasi pribadi, risiko berinteraksi dengan orang asing, dan konsekuensi dari menyebarkan konten tertentu.
- Kurangnya Pengawasan dan Pendampingan Orang Tua: Orang tua yang tidak aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas online anak-anak, atau kurangnya komunikasi terbuka mengenai pengalaman daring anak, dapat membuat anak lebih rentan. Lemahnya perlindungan yang diberikan oleh keluarga menjadi salah satu penyebab utama (Asmaret, 2020).
- Tekanan Teman Sebaya (Peer Pressure): Dorongan untuk ikut tren, memiliki banyak pengikut, atau mendapatkan validasi online dapat membuat anak mengambil risiko yang tidak perlu.
- Anonimitas dan Kemudahan Akses bagi Pelaku: Internet memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas asli mereka, sehingga lebih mudah melakukan manipulasi dan kejahatan tanpa terdeteksi secara langsung.
D. Analisis Penyebab Umum Kekerasan Terhadap Anak dan Relevansinya di Era Digital
Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak secara umum juga memiliki relevansi dalam konteks digital:
- Kultur Kekerasan dan Paradigma Keliru: Anggapan bahwa anak adalah “milik” orang dewasa yang harus tunduk, atau bahwa kekerasan adalah bagian dari pendisiplinan, dapat termanifestasi dalam pengawasan online yang terlalu mengekang secara kasar atau sebaliknya, pembiaran total. Pepatah “di ujung rotan ada emas” adalah paradigma keliru yang harus diluruskan (Seto Mulyadi).
- Stres dan Tekanan Hidup Orang Tua: Faktor ekonomi, konflik rumah tangga, atau stres akibat modernisasi yang tidak terkendali dapat mengurangi kualitas pengasuhan dan pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak. Hal ini dapat membuat anak mencari pelarian atau pengakuan di dunia maya tanpa bimbingan yang memadai.
- Karakter Psikologis Pelaku: Individu dengan kecenderungan predator atau sadistik menemukan media baru di internet untuk menyalurkan hasrat negatif mereka, memanfaatkan anonimitas dan jangkauan global.
- Disfungsi Keluarga dan Pola Asuh: Pola asuh otoriter atau permisif yang ekstrem (Baumrind, 1991), serta disfungsi keluarga di mana peran orang tua tidak berjalan sebagaimana mestinya (Sumiadji As’yari, 2019), dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban.
- Paparan Konten Negatif: Tayangan kekerasan atau pornografi di media, termasuk internet, dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku anak, serta menjadi inspirasi bagi pelaku (Tempo, 2006).
- Faktor dari Anak dan Orang Tua: Stres yang berasal dari kondisi anak (misalnya, anak berkebutuhan khusus) atau dari orang tua (misalnya, riwayat menjadi korban kekerasan, gangguan jiwa) dapat berkontribusi pada dinamika kekerasan (Sihotang, 2004; UNICEF, 1986).
E. Strategi Pencegahan dan Penanganan Komprehensif
Menghadapi ancaman kekerasan terhadap anak di era digital memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan berbagai pihak (KemenPPPA, 2024).
- Pendidikan dan Literasi Digital (untuk Anak dan Orang Tua):
- Anak: Memberikan edukasi berkelanjutan tentang keamanan di dunia maya, pentingnya privasi, cara mengenali tanda-tanda grooming dan cyberbullying, berpikir kritis terhadap informasi online, dan mekanisme pelaporan yang aman.
- Orang Tua: Meningkatkan kesadaran dan keterampilan orang tua dalam mendampingi anak di dunia digital (digital parenting), membangun komunikasi terbuka, serta memahami teknologi yang digunakan anak (Lansford, J. E., et.al., 2011).
- Pengawasan Aktif dan Komunikasi Terbuka oleh Orang Tua:
- Melakukan pengawasan yang proporsional dan suportif terhadap penggunaan internet dan media sosial anak.
- Membangun diskusi dua arah tentang konten yang dilihat anak dan interaksi yang mereka lakukan, tanpa menghakimi.
- Penguatan Manajemen Kasus dan Layanan Perlindungan Anak:
- Memperkuat sistem pelaporan kasus kekerasan yang ramah anak dan mudah diakses (contoh: SIMFONI-PPA).
- Menyediakan layanan pendampingan psikologis, medis, dan hukum yang komprehensif bagi anak korban kekerasan, baik di dunia luring maupun daring.
- Menyediakan rumah aman (shelter) bagi korban yang membutuhkan.
- Keterlibatan Komunitas, Sekolah, dan Lembaga Keagamaan:
- Menggalang kerjasama antara keluarga, sekolah, dan komunitas (termasuk lembaga keagamaan) untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif.
- Sekolah dapat mengintegrasikan literasi digital dan anti-bullying ke dalam kurikulum.
- Pemuka agama dan komunitas dapat berperan dalam edukasi moral dan etika digital.
- Peraturan, Regulasi, dan Penegakan Hukum yang Tegas:
- Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kekerasan daring, memberikan efek jera.
- Memastikan adanya regulasi yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi terkait kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan perlindungan data pribadi anak.
- Mendorong platform digital untuk bertanggung jawab dalam memoderasi konten dan menyediakan fitur keamanan yang lebih baik.
Kekerasan terhadap anak di era digital adalah masalah serius dan kompleks yang mengancam kesejahteraan dan masa depan generasi penerus. Berbagai bentuk kekerasan daring seperti cyberbullying, grooming, penyebaran konten seksual tanpa izin, serta pelecehan dan eksploitasi seksual online, memiliki dampak multidimensional yang merusak, mulai dari gangguan psikologis berat hingga risiko kekerasan fisik. Faktor-faktor seperti kebutuhan anak untuk bersosialisasi, kurangnya literasi digital, dan minimnya pengawasan orang tua berkontribusi pada kerentanan mereka.
Data prevalensi kekerasan terhadap anak di Indonesia, termasuk yang terjadi di ranah daring, menunjukkan urgensi untuk tindakan segera dan komprehensif. Upaya pencegahan dan penanganan tidak bisa lagi bersifat parsial, melainkan harus melibatkan sinergi dari berbagai pihak: keluarga sebagai garda terdepan dalam pengasuhan dan pendampingan; institusi pendidikan dalam membekali anak dengan literasi digital dan karakter yang kuat; komunitas dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang peduli; serta pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyediakan payung regulasi yang kuat, layanan perlindungan yang responsif, dan penindakan tegas terhadap pelaku.
Sebagaimana ditekankan oleh Menteri PPPA, kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan partisipasi, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak PBB dan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia. Hanya dengan komitmen bersama, kita dapat melindungi anak-anak dari bayang-bayang kekerasan di era digital dan memastikan mereka dapat meraih potensi terbaiknya.
Saran
- Bagi Orang Tua: Tingkatkan literasi digital pribadi, bangun komunikasi terbuka dan penuh empati dengan anak mengenai aktivitas online mereka, gunakan perangkat lunak kontrol orang tua secara bijak, dan jadilah model perilaku digital yang bertanggung jawab.
- Bagi Institusi Pendidikan: Integrasikan kurikulum literasi digital, keamanan siber, dan pencegahan bullying (termasuk cyberbullying) secara komprehensif. Ciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan suportif di sekolah.
- Bagi Pemerintah dan Legislator: Kaji ulang dan perkuat regulasi terkait perlindungan anak di ruang siber, termasuk penanganan konten ilegal dan penindakan pelaku. Alokasikan sumber daya yang memadai untuk program pencegahan, layanan korban, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
- Bagi Penyedia Platform Digital: Bertanggung jawab dalam mengembangkan fitur keamanan yang lebih proaktif, mempermudah pelaporan konten berbahaya, dan bekerja sama dengan otoritas dalam penanganan kasus kekerasan anak online.
- Bagi Anak dan Remaja: Bekali diri dengan pengetahuan tentang risiko online, berani menolak ajakan atau tekanan yang tidak nyaman, dan segera laporkan kepada orang dewasa yang dipercaya jika mengalami atau menyaksikan kekerasan daring.
Daftar Pustaka
- Asmaret, D. (2020). Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan Terhadap Anak di Era Digital. Journal IAIN Sultan Amai Gorontalo. (Diambil dari informasi yang diberikan).
- Baumrind, D. (1991). Effective parenting during the early adolescent transition. In P. A. Cowan & M. Hetherington (Eds.), Family transitions (111-163).
- Harian Kedaulatan Rakyat. (2009). (Sebagaimana dikutip dalam teks).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). Data SIMFONI-PPA Tahun 2024. Jakarta: KemenPPPA.
- KemenPPPA. (2024, 3 Juli). Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan. Diakses dari kemenpppa.go.id.
- Lansford, J. E., et.al. (2011). Parenting and child development in non-Western cultures. Child Development Perspectives, 5(3), 202-208.
- Plato Foundation. (2024, 22 Juli). Yayasan PLATO dan Mitra Memperkuat Perlindungan Anak. (Sebagaimana dikutip dalam teks).
- PSGA UIN Malang. (2025, 14 Februari). Menghadapi Tantangan Kekerasan Seksual Anak di Era Digital. Diakses dari psga.uin-malang.ac.id.
- Redbridge SCP. Jenis-jenis Kekerasan. Diakses dari redbridgescp.org.uk. (Sebagaimana dikutip dalam teks).
- RRI.co.id. (2024, 31 Agustus). Kekerasan Anak di Ruang Digital. (Sebagaimana dikutip dalam teks).
- Sihotang. (2004). (Sebagaimana dikutip dalam teks mengenai penyebab kekerasan).
- Studi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kekerasan terhadap Anak. (2006). (Sebagaimana dikutip dalam teks).
- Sumiadji As’yari. (2019). (Sebagaimana dikutip dalam teks mengenai hasil pengaduan KOMNAS Perlindungan Anak).
- Tempo. (2006). (Sebagaimana dikutip dalam teks mengenai pengaruh tayangan televisi).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 1 Anak.
- UNICEF. (1986). (Sebagaimana dikutip dalam teks mengenai faktor pemicu kekerasan anak oleh orang tua).
- UNICEF Indonesia. (2024). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR). Jakarta: UNICEF & BPS.
- UNICEF & Save the Children. Guidelines for the Clinical Management of Child Abuse Cases. (Sebagaimana dikutip sebagai sumber definisi).